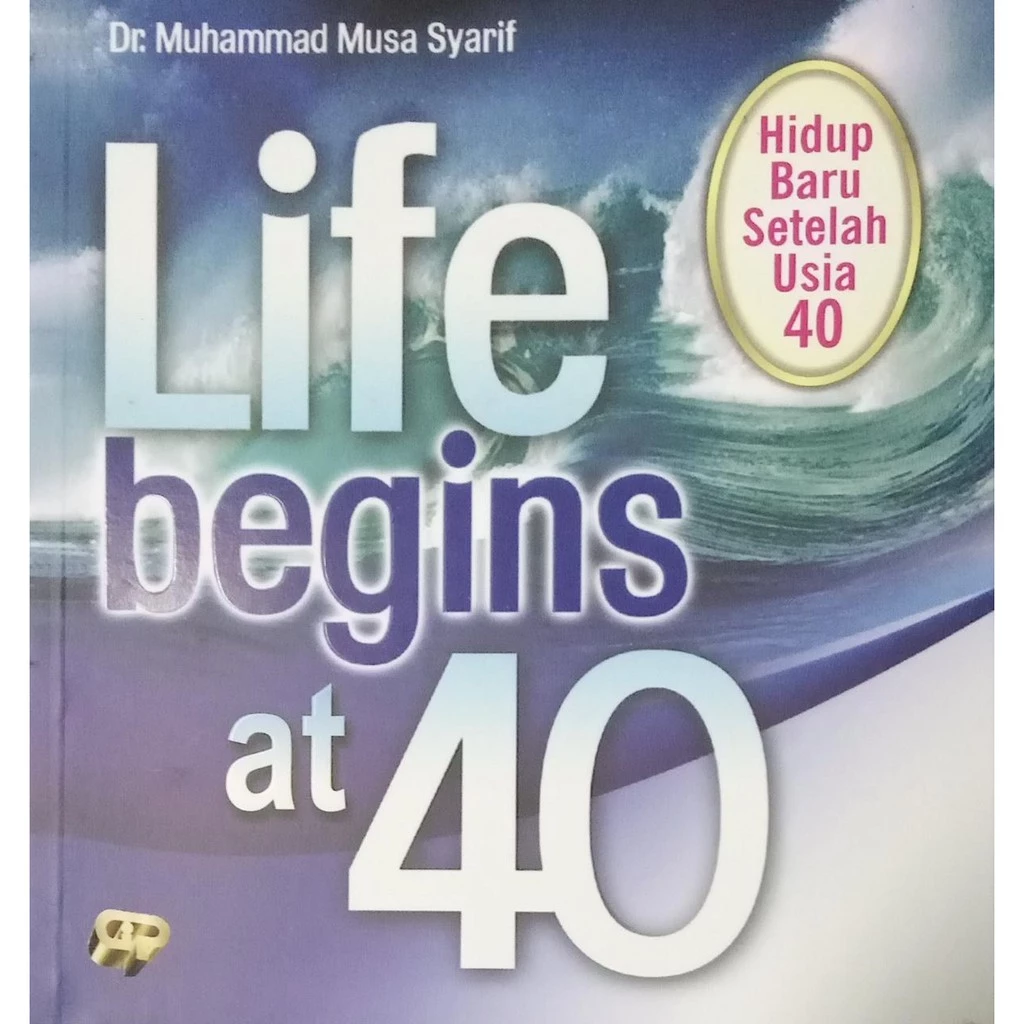Ada masa ketika saya bangun pagi dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, meski saya tidak tahu persis apa. Hidup berjalan, tanggung jawab terpenuhi, orang-orang di sekitar baik-baik saja. Namun di dalam diri, selalu ada dorongan halus untuk membenahi sesuatu. Pikiran terasa sibuk mencari bagian mana yang kurang, mana yang belum beres, mana yang seharusnya bisa dibuat lebih baik.
Di usia yang lebih muda, dorongan itu terasa wajar. Bahkan dianggap sebagai tanda kemajuan. Kita diajarkan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas, mengejar versi terbaik. Tapi entah sejak kapan, terutama setelah melewati usia empat puluh, dorongan itu mulai terasa melelahkan. Bukan karena hidup semakin berat, melainkan karena kesadaran kita mulai berubah.
Saya mulai menyadari bahwa tidak semua hal yang terasa tidak nyaman harus segera diperbaiki. Tidak semua kegelisahan adalah masalah. Tidak semua ketidaksempurnaan adalah kegagalan.
Kesadaran itu tidak datang sekaligus. Ia muncul perlahan, melalui rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan, melalui kekecewaan yang tidak lagi meledak, melalui keinginan sederhana untuk berhenti sejenak dan bertanya: apakah ini benar-benar rusak, atau saya hanya terlalu terbiasa ingin mengendalikan segalanya?
Ada masa ketika saya merasa bertanggung jawab atas semua hal. Atas perasaan orang lain, atas keputusan masa lalu, atas arah hidup yang tidak selalu sesuai rencana. Setiap ketidaknyamanan terasa seperti kesalahan pribadi. Dan setiap kesalahan seolah menuntut perbaikan segera.
Namun semakin saya berusaha membenahi semuanya, semakin terasa bahwa hidup tidak menjadi lebih ringan. Justru sebaliknya, saya menjadi lebih tegang. Lebih mudah menyalahkan diri. Lebih sulit menikmati hal-hal sederhana yang sebenarnya masih utuh.
Di titik itu, saya mulai jujur pada diri sendiri. Mengakui bahwa ada bagian hidup yang tidak bisa — dan mungkin tidak perlu — diperbaiki. Ada relasi yang berubah bukan karena salah siapa-siapa, tetapi karena waktu memang mengubah kita. Ada impian yang tidak terwujud bukan karena kita kurang berusaha, melainkan karena hidup membawa kita ke arah lain. Ada sifat dalam diri yang tidak sepenuhnya bisa dihilangkan, hanya bisa dipahami.
Pengakuan ini tidak mudah. Ada rasa kalah yang samar. Seolah menerima berarti menyerah. Seolah tidak memperbaiki berarti tidak peduli. Padahal, di situlah perbedaan halus yang mulai saya pahami.
Menerima bukan berarti membiarkan diri rusak. Menerima berarti berhenti memaksa hidup untuk selalu sesuai dengan gambaran kita. Ada kebijaksanaan dalam mengakui bahwa sebagian hal hanya perlu dihadapi dengan kehadiran, bukan dengan perlawanan.
Saya melihat ini dalam hubungan dengan orang-orang terdekat. Dulu, saya sering merasa perlu “meluruskan” perbedaan. Menjelaskan, meyakinkan, memperbaiki kesalahpahaman. Sekarang, saya mulai belajar bahwa tidak semua perbedaan harus diselesaikan. Beberapa cukup dipahami. Beberapa cukup dihormati. Hubungan justru terasa lebih tenang ketika saya berhenti merasa bertugas untuk membetulkan segalanya.
Hal yang sama terjadi dalam memandang diri sendiri. Ada bagian dari masa lalu yang dulu ingin saya perbaiki, seandainya bisa diulang. Pilihan yang terasa keliru. Keputusan yang berujung penyesalan. Tapi seiring waktu, saya mulai melihat bahwa masa lalu tidak menunggu untuk diperbaiki. Ia hanya ingin diterima sebagai bagian dari perjalanan.
Penerimaan ini membawa kejernihan yang tidak saya temukan dalam usaha keras. Hidup terasa lebih lapang ketika saya berhenti menginventarisasi kekurangan. Ketika saya membiarkan beberapa pertanyaan tetap tanpa jawaban. Ketika saya mengizinkan diri berada di fase “cukup”, bukan “harus lebih”.
Di usia ini, saya mulai percaya bahwa kedewasaan bukan tentang seberapa banyak yang kita benahi, melainkan seberapa jujur kita melihat apa yang memang tidak perlu diubah. Ada ketenangan yang muncul saat kita tidak lagi sibuk mengutak-atik hidup, tetapi mulai mendengarkannya.
Menerima bahwa tidak semua hal perlu diperbaiki juga mengubah cara saya memandang hari-hari biasa. Pagi yang tidak produktif tidak lagi terasa sebagai kegagalan. Perasaan lelah tidak langsung ditafsirkan sebagai kelemahan. Diam tidak selalu berarti kehilangan arah. Semua itu menjadi bagian wajar dari hidup yang bergerak naik-turun.
Saya tidak mengatakan bahwa kita berhenti bertumbuh. Penerimaan bukan akhir dari perubahan. Justru sebaliknya, ia adalah dasar yang lebih jujur untuk bertumbuh. Perubahan yang lahir dari penerimaan terasa lebih manusiawi, lebih sabar, dan lebih selaras dengan diri sendiri.
Ada kebebasan kecil yang muncul ketika kita berhenti bertanya “apa yang salah?” dan mulai bertanya “apa yang sedang terjadi?” Pertanyaan kedua tidak menuntut perbaikan. Ia hanya mengundang kehadiran.
Kini, ketika ada hal yang terasa tidak beres, saya mencoba tidak langsung bereaksi. Saya duduk bersamanya sebentar. Mendengarkan rasa tidak nyaman itu tanpa buru-buru memberi label. Kadang, setelah diberi ruang, perasaan itu melembut dengan sendirinya. Kadang, ia tetap ada. Dan itu pun tidak apa-apa.
Hidup, saya belajar, tidak selalu menunggu kita untuk memperbaikinya. Kadang ia hanya ingin kita berhenti sejenak, menurunkan ekspektasi, dan hadir apa adanya.
Mungkin di usia empat puluh ke atas, kebijaksanaan bukan lagi soal menemukan jawaban baru, tetapi soal mengurangi kebutuhan untuk selalu menjawab. Bukan tentang membentuk hidup agar ideal, tetapi tentang berdamai dengan kenyataan yang sudah cukup.
Dan di sana, tanpa banyak usaha, tanpa banyak perbaikan, saya menemukan sesuatu yang lama saya cari: ketenangan yang tidak bergantung pada kesempurnaan.